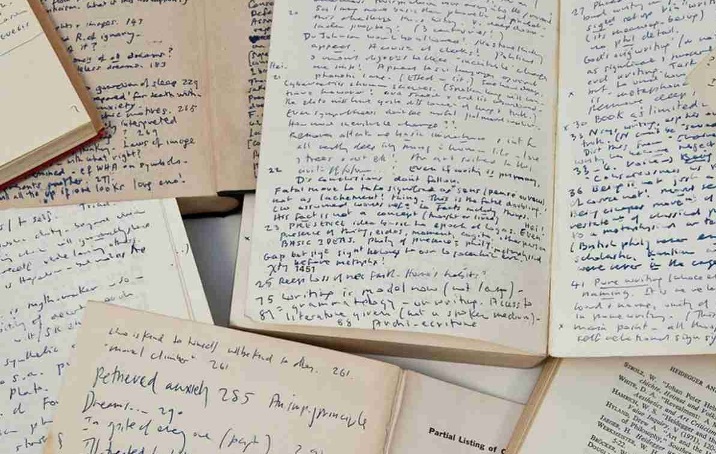Interpretasi (interpretation) adalah proses penafsiran atau pemaknaan terhadap data maupun fakta sejarah. Interpretasi terdiri dari dua jenis yakni analisis (menguraikan) dan sistesis (menyatukan).[1] Interpretasi umumnya dilakukan untuk menguraikan sesuatu yang belum jelas. Dalam tahap interpretasi, diperlukan daya imajinasi yang kuat. Kemampuan imajinasi terhadap peristiwa masa lalu akan turut memberi keluasan dan warna historiografi. Tidak heran bila dewasa ini banyak kajian sejarah dan ilmu-ilmu sosial lain mengangkat topik yang sifatnya menafsir kembali, menginterpretasi kembali, atau menginterpretasi ulang. Penafsiran kembali ini dalam bahasa yang lebih keren disebut ‘reinterpretasi’.
Karena melewati proses interpretasi (penafsiran), maka peluang munculnya tulisan sejarah dengan berbagai versi sangat terbuka. Hal ini umumnya tidak bisa dilepaskan dari latar belakang agama, politik, ideologi, budaya maupun jiwa zaman dari penginterpretasi. Hal yang wajar bila sejarah G30S tahun 1965 misalnya ada beberapa versi yakni Soekarno, Amerika Serikat, Angkatan Darat, Angkatan Udara, maupun PKI. Bahkan dengan sumber sejarah yang sama pun bisa melahirkan narasi yang berbeda akibat hasil interpretasi yang berbeda dari masing-masing sejarawan. Sebagai contoh dalam konteks ini adalah adanya beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia.
Dalam menginterpretasi data atau fakta, sejarawan tidak boleh berimajinasi secara liar tak terbatas layaknya sastrawan. Sejarah bukanlah sastra. Interpretasi seorang sejarawan dibatasi oleh data dan fakta yang ada. Bahkan beberapa sejarawan menyatakan bahwa no document no history (meskipun ini tidak sepenuhnya benar karena sumber sejarah tak melulu berwujud dokumen). Untuk itulah, tulisan sejarah yang baik adalah tulisan yang dibuat seobjektif mungkin berdasarkan sumber, data dan fakta yang ada (walaupun subjektivitas itu pasti ada meski dalam kadar yang amat sedikit).
Barang kali salah satu sejarah yang paling sulit ditulis secara objektif adalah sejarah agama. Sejarah ini bisa dibilang sejarah yang paling sulit untuk dinarasikan karena sebagian obyek kajian susah untuk dibuktikan secara empiris. Terdapat gejala-gejala metafisika (baca: gaib) di luar kekuatan manusia yang susah untuk dibuktikan secara empiris meskipun dalam hal tertentu tidak menampik kebenarannya (kebenaran relatif). Karena menyangkut keyakinan, sejarawan acapkali terjebak pada subjektivitas yang tinggi. Keyakinan yang mendalam terhadap agamanya kerap kali menolak segala fakta yang tidak sesuai dengan keinginannya/keimanannya. Dari sinilah sebenarnya kita bisa memilah dan membedakan “sejarah agama” dan “sejarah beragama”.
Hal lain yang sekiranya juga tidak kalah penting diperhatikan seorang sejarawan dalam menginterpretasi data atau fakta adalah generalisasi dan simplifikasi. Generalisasi adalah proses penyimpulan secara umum fakta-fakta yang ada. Sejarawan harus hati-hati benar dalam membuat pernyataan (simpulan interpretasi) karena ciri khas dari sejarah justru mencari ‘keunikan’ dari setiap peristiwa masa lalu (berbeda halnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya yang justru mencari keumuman). Generalisasi umumnya lebih mudah dilakukan dalam konteks “pola sejarah”, bukan detail peristiwa sejarah. Adapun simplifikasi (reduksionisme) adalah proses penyederhanaan simpulan interpretasi. Hal ini akan celaka ketika fakta sebenarnya justru kompleks. Artinya, sejarawan telah melakukan blunder simpulan interpretasi terkait faktor atau gejala sejarah yang sebenarnya lebih kompleks tetapi kemudian direduksi atau disederhanakan seolah-olah hanya melibatkan satu atau dua faktor saja. Generalisasi dan simplifikasi yang tidak tepat bisa melahirkan ‘kesesatan’ (mitos sejarah).
Kelanjutan dari interpretasi adalah “eksplanasi sejarah” (historical explanation). Eksplanasi sejarah adalah penjelasan atau keterangan lebih rinci mengenai hubungan (utamanya sebab-akibat) suatu peristiwa atau fakta-fakta masa lampau bisa terjadi atau mempengaruhi peristiwa lain.[2] Eksplanasi sejarah tidak sekedar menguraikan fakta sejarah secara deskriptif melainkan secara analitik terutama dalam menjawab pertanyaan why (mengapa) dan how (bagaimana). Di sinilah penguasaan konsep dan teori begitu diperlukan sebagai “pisau analisis” untuk menyelami secara mendalam sebuah hubungan atau keterkaitan antara fakta satu dengan fakta lainnya. Fungsi eksplanasi sejarah adalah memberikan narasi sejarah yang tidak setengah-setengah (pernyataan yang tanggung dan menimbulkan rasa penasaran) melainkan narasi yang lengkap, jelas, mendalam dan argumentatif.
Historiografi
Historiografi (historiography) merupakan term yang terbentuk dari dua akar kata yakni history (sejarah) dan graph (tulisan). Dilihat dari kata penyusun ini secara sederhana historiografi berarti “tulisan sejarah”. Namun dalam pandangan dan pengertian yang lebih luas, historiografi tidak hanya dimaknai sebagai tulisan sejarah (hasil karya) melainkan “proses penulisan sejarah (hasil karya) itu sendiri”. Gootschalk mengartikan historiografi sebagai usaha penulisan kembali data sejarah menjadi kisah dan menyajikan dalam bentuk buku sejarah atau artikel.[3] Dalam konteks ini historiografi dimaknai sebagai sebuah kesatuan antara proses dan juga hasil akhir (tulisan sejarah).
Historiografi adalah tahap terakhir penyajian suatu tulisan sejarah secara utuh. Historiografi merupakan tahap keempat dalam alur metodologi sejarah setelah melewati tahap heuristik, kritik, dan interpretasi. Sebagai analogi, historiografi adalah wujud penyajian hidangan makan malam kepada publik yang telah melewati tahap penentuan menu, pemilihan bahan makanan, penentuan bumbu, dan tahap imajinasi rasa serta penyajian. Dari penyajian hidangan ini akan terlihat bagaimana kerapian, ketelitian, kesistematisan, pola atau seni penyajian, keselarasan antar jenis makanan yang dihidangkan, dan tentunya rasa dari hidangan itu sendiri. Dalam analogi karya, historiografi adalah produk akhir yang siap dipasarkan atau disuguhkan kepada khalayak.
Dalam dunia akademis, dikenal adanya beberapa jenis historiografi. Dilihat dari sisi nasionalismenya, terdapat historiografi Indonesiasentris. Jenis historiografi ini biasanya kerap dibenturkan dengan historiografi kolonialsentris (Nerlandosentris). Perbedaan dari dua historiografi ini terletak pada penempatan subyek sejarah. Adapun dilihat dari cakupan pembahasannya, ada historiografi Annales (total history) dan historiografi non-Annales. Sedangkan dilihat dari ruang lingkup geografisnya, terdapat historiografi lokal dan nasional.
Semua orang yang menulis sejarah bisa disebut sejarawan (historian). Dokter, guru kimia, guru matematika, tukang bengkel, pedagang, dosen geografi, atau siapapun yang menulis sejarah bisa disebut sejarawan. Label sejarawan mengikat pada produk yang dihasilkan yakni tulisan sejarah (historiografi). Asal produk yang dihasilkan adalah tulisan sejarah (cerita atau kisah mengenai peristiwa masa lalu) maka bisa disebut sejarawan. Namun perlu diketahui bahwa terdapat dua jenis sejarawan yang kita kenal selama ini. Mereka adalah “sejarawan profesional (akademis)” dan “sejarawan non-profesional”.
Sejarawan profesional (sejarawan sungguhan) umumnya disandang oleh mereka yang memiliki latar belakang pendidikan formal jurusan sejarah (terutama murni). Mereka diberi bekal ketat prinsip-prinsip metodologi sejarah. Sedangkan sejarawan non-profesional (sejarawan amatiran) adalah siapa saja yang tidak berlatar belakang pendidikan formal jurusan sejarah. Namun demikian, ada juga sejarawan yang tidak berlatar belakang pendidikan formal sejarah tetapi hasil karyanya sama bagusnya bahkan lebih bagus dari pada hasil karya sejarawan berlatar belakang pendidikan formal jurusan sejarah. Bahkan tidak sedikit pula sejarawan berlatar belakang pendidikan formal sejarah yang justru mandul dan kualitas karyanya lebih buruk dari sejarawan yang dilabeli non-profesional. Ini berarti sejarawan yang berlatarbelakang pendidikan formal sejarah justru tidak profesional. Dapat disimpulkan bahwa generalisasi sejarawan profesional dan non-profesional ini bersifat umumnya (kebanyakan), bukan mutlak semuanya.
Umumnya terdapat perbedaan antara sejarawan profesional dan sejarawan yang bukan profesional. Perbedaan tersebut setidaknya bisa dilihat dari dua hal yakni proses dan hasil tulisan. Sejarawan non-profesional umumnya tidak atau kurang ketat dalam memegang prinsip atau langkah-langkah metodologis penelitian sejarah. Mereka juga kurang bisa menempatkan kegunaan sumber primer maupun sekunder. Pada aspek yang lain, mereka juga sering kali terjebak pada subyektivitas yang tinggi. Tulisan pun cenderung kurang analistik, kurang sistematis, dan bercampur “mitos-mitos sejarah”.
Menurut Sartono dalam proses penulisan sejarah diperlukan pendekatan, metode, dan gaya bahasa serta isi penulisannya harus dapat dipertanggungjawabkan.[4] Pendekatan berkaitan dengan cara pandang yang ingin digunakan saat menganalisis dan menuliskan sebuah kisah. Adapun metode dalam menulis sejarah setidaknya bisa dilakukan melalui dua cara. Pertama, tematik-kronologis. Sejarawan bisa menetapkan terlebih dahulu tema-tema atau sub-tema dalam menyusun sebuah karya besar seperti buku, skripsi, tesis, atau desertasi. Setelah tema-tema atau sub-tema ditentukan, tiba gilirannya mengisahkan peristiwa masa lalu secara kronologis (urut berdasarkan waktu) di masing-masing tema atau sub-tema tersebut. Kedua, serial–kronologis. Sejarawan bisa menulis langsung secara kronologis tanpa mempertimbangkan tema-tema khusus (spesifik). Metode penulisan krononologis lebih bersifat mengalir, yang penting disusun berdasar alur waktu peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Meminjam istilah Kuntowijoyo (2013: i), sejarah itu diakronis (memanjang dalam waktu), bukan sinkronis (memanjang dalam ruang). Sejarah itu ideographic (terikat waktu dan ruang) bukan nomothetic (tidak terikat waktu dan ruang).[5]
Beberapa hal atau aspek utama yang perlu diperhatikan dalam penulisan sejarah (historiografi) di antaranya: (1) diakronitas, (2) kesesuaian antar kalimat, (3) pemilihan bahasa, diksi dan retorika, (4) penulisan waktu (tahun dan abad), (5) data sebagai daya dukung, (6) apa yang dijanjikan itu yang harus dijawab, (7) penempatan dan kejujuran sumber serta pengutipan, (8) pembedaan sejarah dengan kajian nilai-nilai sejarah. Kedelapan aspek ini setidaknya menjadi indikator penting dalam melihat apakah sebuah historiografi disajikan secara optimal atau tidak.
[1] Herlina, N. Metode Sejarah. Bandung: Satya Historika, 2011: 15; Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013: 78-79.
[2] Salah satu tulisan bagus mengenai eksplanasi sejarah lihat Kuntowijoyo. (2008). Penjelasan Sejarah (Historical Explanation). Yogyakarta: Tiara Wacana. Baca pula Sjamsuddin, Helius. Metodologi Sejarah. Jakarta: Depdikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1996: 23.
[3] Gottschalk, Luis. Mengerti Sejarah (Pengantar Metode Sejarah). Jakarta: UI, 1975: 33
[4] Kartodirdjo, Sartono. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. Yogjakarta: Ombak, 2014: 21.
[5] Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013: i.